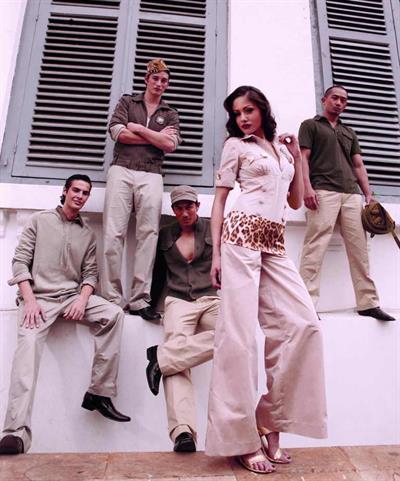
Ratna Djuwita, psikolog sosial dari Universitas Indonesia mengatakan, kelas menengah kita mungkin baru akan bergerak kalau mereka sudah ‘terinjak’. Maksudnya, kalau kepentingan dan kenyamanan mereka sudah mulai terusik. Sementara sekarang ini semua aspek kehidupan –terutama kegiatan ekonomi —secara umum masih berjalan lancar-lancar saja, dan kegiatan mereka dalam mencari uang, mengaktualisasikan diri, dan bersenang-senang juga belum terganggu.
Namun Ratna juga melihat alasan lain mengapa kelas menengah kita terkesan pasif dan tidak peduli. “Tingkat kepercayaan mereka sangat rendah terhadap pemerintah, para wakil rakyat, birokrasi. Ibaratnya, mereka sudah mengalami disorientasi, tidak tahu lagi mana yang benar dan salah, siapa yang bisa dipercaya, dan kepada siapa bisa meminta perlindungan, karena aparat hukum dan keamanan pun kini tidak lagi bisa ‘dipegang’ dan diandalkan.”
Ada yang beranggapan, kelas menengah kita bersikap tak peduli karena mereka merasa berjuang sendiri, tidak pernah mendapat dukungan fasilitas apa pun dari pemerintah. Karena itu, mereka tak merasa berutang budi pada pemerintah. Fajar tidak menolak anggapan itu. “Memang, bisa dibilang semua aspek kehidupan di Indonesia ini sesungguhnya bisa jalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Tapi, bukan berarti pemerintah tak punya andil sama sekali. Setidaknya, pemerintah sekarang telah membuka keran demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Apakah kita mau seperti kelas menengah di Cina, di mana pemerintahnya memberi dukungan fasilitas penuh, tetapi menutup rapat-rapat keran demokrasi?” Fajar balik bertanya.
Ia menekankan, kalau kelas menengah kita baru bergerak hanya kalau sudah ‘terinjak’, dikhawatirkan pada saat itu terjadi, semua sudah terlambat. Bisa jadi pilar pluralitas di negeri kita sudah telanjur porak poranda. Karena itu, Fajar mengajak kaum kelas menengah agar mulai menunjukkan kepedulian mereka dengan langkah-langkah yang lebih kongkret, bukan sekadar mengomel dan ‘merepet’ di media sosial.
Untuk mengimbangi gerakan-gerakan anti-toleransi tersebut, tentunya kita tidak perlu ikut-ikutan memilih langkah ‘garis keras’. Kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan bidang keahlian dan kapasitas masing-masing. Kalau bergerak di bidang sineas, misalnya, langkah sutradara Garin Nugroho atau Hanung Bramantyo mungkin bisa dijadikan contoh. Melalui film Mata Tertutup (Garin) dan Tanda Tanya (Hanung), keduanya ikut berkontribusi menyebarkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme pada masyarakat.
Atau seperti yang dilakukan Maarif Institute, yang (antara lain) mendanai pembuatan film Mata Tertutup (mengisahkan para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka yang terjerat dalam kegiatan Negara Islam Indonesia) serta baru-baru ini menerbitkan buku berjudul Pendidikan Karakter yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan antikekerasan untuk siswa SMA. Buku pengayaan materi ini sudah berhasil masuk kurikulum di SMA-SMA se-Kotamadya Surakarta, Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Cianjur.
“Meski skalanya kecil-kecil, tapi kalau kita mengusungnya bersama-sama dan secara terus menerus, pasti akan membawa dampak signifikan,” tutur Fajar, yang mengistilahkannya sebagai ‘pertempuran kecil-kecilan’, untuk menunjukkan adanya perlawanan terhadap nilai-nilai anti-toleransi yang belakangan ini makin marak diteriakkan. Mungkin dari situ akan muncul tokoh-tokoh pejuang toleransi dan pluralitas yang menonjol dan berpengaruh, yang bisa menggerakkan massa untuk melakukan perlawanan yang bersifat massal.
Tentu bukannya tanpa risiko sama sekali. Hanung, misalnya, pernah mendapat ancaman dari ormas keagamaan tertentu yang menolak penayangan film tersebut. Atau Prof. Dr. Musdah Mulia, cendekiawan muslim yang aktif memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme, yang konon sering mendapat ‘teror’ dari pihak-pihak tertentu. “Risikonya tentu ada, tapi kalau kita akhirnya tidak melakukan apa-apa hanya karena takut, memang itulah yang diharapkan oleh kelompok-kelompok anti-toleransi tersebut. Sama seperti yang dilakukan oleh Orde Baru dulu, mereka memang ‘memainkan’ rasa takut masyarakat. Masyarakat yang ketakutan dengan mudah dikuasai. Jadi kalau kita takut, itu sama artinya kita sudah kalah sebelum bertempur,” kata Fajar.
Yang perannya juga sangat penting adalah media massa. Fajar menganggap, peran media massa sesungguhnya sangat powerful untuk membentuk opini masyarakat. Sayangnya, sekarang ini media massa masih lebih suka memberitakan aksi-aksi atau pernyataan-pernyataan kontroversial yang diteriakkan kelompok-kelompok anti-toleransi dan anti-pluralitas, karena dianggap lebih menjual. Akibatnya, kelompok-kelompok ini justru makin terekspos. Sebaliknya, aksi-aksi perdamaian yang dilakukan oleh kelompok pro-toleransi dan pro-pluralitas –yang sesungguhnya tak kalah banyak— jarang diberitakan oleh media massa, mungkin karena dianggap kurang ‘seksi’.
Namun Ratna juga melihat alasan lain mengapa kelas menengah kita terkesan pasif dan tidak peduli. “Tingkat kepercayaan mereka sangat rendah terhadap pemerintah, para wakil rakyat, birokrasi. Ibaratnya, mereka sudah mengalami disorientasi, tidak tahu lagi mana yang benar dan salah, siapa yang bisa dipercaya, dan kepada siapa bisa meminta perlindungan, karena aparat hukum dan keamanan pun kini tidak lagi bisa ‘dipegang’ dan diandalkan.”
Ada yang beranggapan, kelas menengah kita bersikap tak peduli karena mereka merasa berjuang sendiri, tidak pernah mendapat dukungan fasilitas apa pun dari pemerintah. Karena itu, mereka tak merasa berutang budi pada pemerintah. Fajar tidak menolak anggapan itu. “Memang, bisa dibilang semua aspek kehidupan di Indonesia ini sesungguhnya bisa jalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Tapi, bukan berarti pemerintah tak punya andil sama sekali. Setidaknya, pemerintah sekarang telah membuka keran demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Apakah kita mau seperti kelas menengah di Cina, di mana pemerintahnya memberi dukungan fasilitas penuh, tetapi menutup rapat-rapat keran demokrasi?” Fajar balik bertanya.
Ia menekankan, kalau kelas menengah kita baru bergerak hanya kalau sudah ‘terinjak’, dikhawatirkan pada saat itu terjadi, semua sudah terlambat. Bisa jadi pilar pluralitas di negeri kita sudah telanjur porak poranda. Karena itu, Fajar mengajak kaum kelas menengah agar mulai menunjukkan kepedulian mereka dengan langkah-langkah yang lebih kongkret, bukan sekadar mengomel dan ‘merepet’ di media sosial.
Untuk mengimbangi gerakan-gerakan anti-toleransi tersebut, tentunya kita tidak perlu ikut-ikutan memilih langkah ‘garis keras’. Kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan bidang keahlian dan kapasitas masing-masing. Kalau bergerak di bidang sineas, misalnya, langkah sutradara Garin Nugroho atau Hanung Bramantyo mungkin bisa dijadikan contoh. Melalui film Mata Tertutup (Garin) dan Tanda Tanya (Hanung), keduanya ikut berkontribusi menyebarkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme pada masyarakat.
Atau seperti yang dilakukan Maarif Institute, yang (antara lain) mendanai pembuatan film Mata Tertutup (mengisahkan para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka yang terjerat dalam kegiatan Negara Islam Indonesia) serta baru-baru ini menerbitkan buku berjudul Pendidikan Karakter yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan antikekerasan untuk siswa SMA. Buku pengayaan materi ini sudah berhasil masuk kurikulum di SMA-SMA se-Kotamadya Surakarta, Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Cianjur.
“Meski skalanya kecil-kecil, tapi kalau kita mengusungnya bersama-sama dan secara terus menerus, pasti akan membawa dampak signifikan,” tutur Fajar, yang mengistilahkannya sebagai ‘pertempuran kecil-kecilan’, untuk menunjukkan adanya perlawanan terhadap nilai-nilai anti-toleransi yang belakangan ini makin marak diteriakkan. Mungkin dari situ akan muncul tokoh-tokoh pejuang toleransi dan pluralitas yang menonjol dan berpengaruh, yang bisa menggerakkan massa untuk melakukan perlawanan yang bersifat massal.
Tentu bukannya tanpa risiko sama sekali. Hanung, misalnya, pernah mendapat ancaman dari ormas keagamaan tertentu yang menolak penayangan film tersebut. Atau Prof. Dr. Musdah Mulia, cendekiawan muslim yang aktif memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme, yang konon sering mendapat ‘teror’ dari pihak-pihak tertentu. “Risikonya tentu ada, tapi kalau kita akhirnya tidak melakukan apa-apa hanya karena takut, memang itulah yang diharapkan oleh kelompok-kelompok anti-toleransi tersebut. Sama seperti yang dilakukan oleh Orde Baru dulu, mereka memang ‘memainkan’ rasa takut masyarakat. Masyarakat yang ketakutan dengan mudah dikuasai. Jadi kalau kita takut, itu sama artinya kita sudah kalah sebelum bertempur,” kata Fajar.
Yang perannya juga sangat penting adalah media massa. Fajar menganggap, peran media massa sesungguhnya sangat powerful untuk membentuk opini masyarakat. Sayangnya, sekarang ini media massa masih lebih suka memberitakan aksi-aksi atau pernyataan-pernyataan kontroversial yang diteriakkan kelompok-kelompok anti-toleransi dan anti-pluralitas, karena dianggap lebih menjual. Akibatnya, kelompok-kelompok ini justru makin terekspos. Sebaliknya, aksi-aksi perdamaian yang dilakukan oleh kelompok pro-toleransi dan pro-pluralitas –yang sesungguhnya tak kalah banyak— jarang diberitakan oleh media massa, mungkin karena dianggap kurang ‘seksi’.
Tina Savitri



